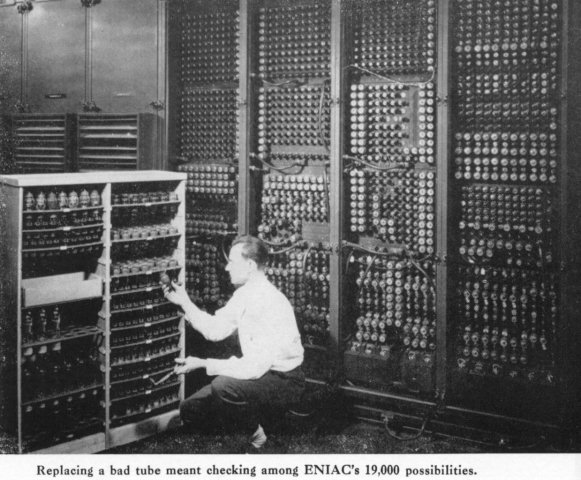Oleh Zulia Ilmawati dkk
(TIM PENDIDIKAN HTI)
Paradigma Pendidikan Nasional
Diakui atau tidak, sistem pendidikan
yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang
sekular-materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada UU
Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagaman, dan khusus.
Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu
pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis
semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang
berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan
melalui penguasaan sains dan teknologi.
Secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui
madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen
Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah
menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola
oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat
bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan oleh Depdiknas
dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama. Pembentukan
karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru
kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar sebagai salah
satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan dari
seluruh aspek.
Hal ini juga tampak
pada BAB X pasal 37 UU Sisdiknas tentang ketentuan kurikulum pendidikan
dasar dan menengah yang mewajibkan memuat 10 bidang mata pelajaran
dengan pendidikan agama yang tidak proposional dan tidak dijadikan
landasan bagi bidang pelajaran yang lainnya. Ini jelas tidak akan mampu
mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional
sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Kacaunya kurikulum ini tentu saja berawal dari asasnya
yang sekular, yang kemudian mempengaruhi penyusunan struktur kurikulum
yang tidak memberikan ruang semestinya bagi proses penguasaan tsaqâfah Islam dan pembentukan kepribadian Islam.
Pendidikan
yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang
menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan
tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian
peserta didik dan penguasaan tsaqâfah
Islam. Berapa banyak lulusan pendidikan umum yang tetap saja 'buta
agama' dan rapuh kepribadiannya? Sebaliknya, mereka yang belajar di
lingkungan pendidikan agama memang menguasai tsaqâfah Islam dan
secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Akan tetapi, di sisi
lain, ia buta terhadap perkembangan sains dan teknologi. Akhirnya,
sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan, dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awam terhadap agama karena orang-orang
yang mengerti agama terkumpul di dunianya sendiri (madrasah, dosen/guru
agama, Depag), tidak mampu terjun di sektor modern.
Sistem
pendidikan yang material-sekularistik tersebut sebenarnya hanyalah
merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang juga sekular. Dalam sistem sekular, aturan-aturan, pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan
untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Karena itu,
di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama.
Mahalnya Biaya Pendidikan
 Pendidikan
bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku
pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga
Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan
lain kecuali tidak bersekolah.
Pendidikan
bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku
pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga
Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan
lain kecuali tidak bersekolah.
Untuk
masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp
1.000.000,- Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA
bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya
pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang
menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada
realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana.
Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan
yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.
Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.
Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu
berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat
implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi
pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan
Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator
kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari
pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan
rakyatnya.
Ko ndisi
ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
(RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk
Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar.
Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan
tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum
yang sosoknya tidak jelas. Munculnya BHMN dan MBS
adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN
sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa
Perguruan Tinggi favorit.
ndisi
ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
(RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk
Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar.
Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan
tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum
yang sosoknya tidak jelas. Munculnya BHMN dan MBS
adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN
sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa
Perguruan Tinggi favorit.
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak
lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran
utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap
tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya,
sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban.
Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Dari
APBN 2005 hanya 5.82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan
dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN
(www.kau.or.id).
Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi
melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib
Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat
dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat
berbentuk badan hukum pendidikan. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.
Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika,
10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti
Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan
menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan
begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi
untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu
saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan
mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk
menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin
terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.
Hal
senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia,
privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah
dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui
Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah
berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan
menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya
sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga
perguruan tinggi.
Bagi
masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi
badan hukum milik negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa
pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di
Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara
berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya
pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan
biaya pendidikan.
Pendidikan
berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang
seharusnya membayarnya. Kewajiban Pemerintahlah untuk menjamin setiap
warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses
masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi,
kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab.
Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah
untuk 'cuci tangan'.
Kualitas SDM yang Dihasilkan Rendah
Akibat
paradigma pendidikan nasional yang materialistik-sekularistik, kualitas
kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Maraknya
tawuran antar remaja di berbagai kota ditambah dengan sejumlah perliku
mereka yang sudah tergolong kriminal, meningkatanya penyalahgunaan
narkoba, dan pergaulan bebas adalah bukti bahwa pendidikan tidak
berhasil membentuk anak didik yang memiliki kepribadian Islam.
Dari
sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain.
Bersama dengan sejumlah negara ASEAN, kecuali Singapura dan Brunei
Darussalam, Indonesia masuk dalam kategori negara yang Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)-nya di tingkat medium. Jika dilihat dari
indikator indeks pendidikan, Indonesia berada di atas Myanmar, Kamboja,
dan Laos atau ada di peringkat 6 negara ASEAN. Bahkan indeks pendidikan
Vietnam—yang pendapatan perkapitanya lebih rendah dari Indonesia—adalah
lebih baik.
Jika
dibandingkan dengan India, sebuah negara dengan segudang masalah
(kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah), ternyata kualitas SDM
Indonesia sangat jauh. India dapat menghasilkan kualitas SDM yang
mencengangkan. Berbekal penguasaannya di dalam teknologi, khususnya
teknologi informasi, negeri dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar
itu mempunyai target menjadi negara maju dan satu dari lima penguasa
dunia pada tahun 2020. Mimpi ini tak muluk-muluk jika kita menengok
kekuatan pendidikannya. Meski negara ini masih bergulat dengan persoalan
buta huruf dan pemerataan pendidikan dasar, India punya sederet
perguruan tinggi yang benar-benar menjadi pusat unggulan dengan reputasi
internasional. Digerakkan oleh keberadaan pusat-pusat unggulan itu,
kini pemerintah India lebih serius membenahi pendidikan masyarakat
bawah.
Prestasi
India dalam teknologi dan pendidikan sangat menakjubkan. Jika Indonesia
masih dibayang-bayangi pengusiran dan pemerkosaan tenaga kerja tak
terdidik yang dikirim ke luar negeri, banyak orang India mendapat posisi
bergengsi di pasar kerja Internasional. Bahkan di AS, kaum profesional
asal India memberi warna tersendiri bagi negara adikuasa itu. Sekitar 30
persen dokter di AS merupakan warga keturunan India. Tidak kurang dari
250 warga India mengisi 10 sekolah bisnis paling top di AS. Sekitar 40
persen pekerja microsoft berasal dari India. (Kompas, 4/9/2004).
Berdasarkan peringkat universitas terbaik di Asia versi majalah Asiaweek 2000,
tidak satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam 20 terbaik. UI
berada di peringkat 61 untuk kategori universitas multidisiplin. UGM
diperingkat 68, UNDIP diperingkat 77, UNAIR diperingkat 75; sedangkan
ITB diperingkat 21 untuk universitas sains dan teknologi, kalah
dibandingkan dengan Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pakistan.
Walaupun
angka partisipasi murni SD di Indonesia dalam kurun 20 tahun meningkat
dari 40 menjadi 100 persen, kualitasnya sulit dibanggakan. Kini puluhan
ribu anak SD harus belajar di sekolah bobrok. Ironinya, sampai saat ini
belum terjawab, bagaimana Pemerintah menangani persoalan yang sangat
kasatmata itu; sementara masih banyak anak usia SD yang putus sekolah
atau malah belum terjangkau sama sekali oleh pelayanan pendidikan. Wajib
belajar 9 tahun secara kuantitatif pun sulit bisa dituntaskan pada
tahun 2008.
 Pendidikan
bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku
pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga
Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan
lain kecuali tidak bersekolah.
Pendidikan
bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku
pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga
Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan
lain kecuali tidak bersekolah.